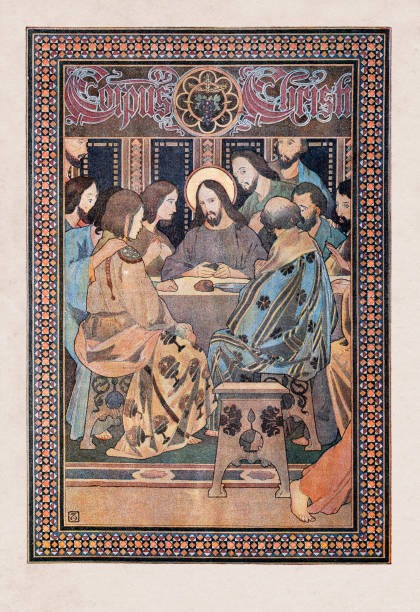Easter Vigil – Easter Sunday [B]
March 31, 2024
Mark 16:1-7
Jesus is either everything or nothing at all. Why? Because He made an extraordinary claim that He is divine. C.S. Lewis responded to this claim with three possible answers, ‘Lunatic, Liar or Lord.’ Either Jesus was a delusional man believing that He was God, or Jesus was an evil man who wanted to deceive the world for His profit, or He is the Lord because what He claimed is true. If Jesus’ claim is true, then He deserves all our worship, our love and adoration. Yet, if Jesus’ claim is false, then He is just nobody who happened to be a lunatic or liar. Then, what is the evidence of His claim?

The answer is the resurrection of Jesus. And what is the proof of His resurrection? The empty tomb! Yes, this is the first evidence we have. If we read the four gospels, we will find a resurrection story with slight variations, but all agree with the reality of the empty tomb. If I were Jesus, I would have chosen a more dramatic and visible way of resurrection. I would have even appeared to Pilate and the chief priests to make a bold statement. Yet, Jesus chose to show an empty tomb and later appeared to the women. But, these women? These women were the same women who stood near the cross of Jesus, and they went back early in the morning to anoint the body of Jesus to give a proper burial to Jesus. These women exhibited their faithfulness and love to Jesus.
The evidence for Jesus’ resurrection has been discussed extensively by many scholars, and I would not have enough time to cover it here. Jesus did not appear to Pilate or Annas and Caiaphas because they had decided to reject Jesus as a lunatic or liar. Thus, Jesus’ resurrection is nothing but useless. They even spread lies that the body was stolen. One scholar said, ‘For disbelievers, no proofs are ever sufficient.’
However, we are here, just like the women who visited the tomb early in the morning. We are here because we believe in Jesus, and we love Him. Jesus’ choice for an empty tomb, rather than a grandeur showoff of His resurrection, invites us to enter the empty tomb and make decisions for ourselves. Pope Francis once said that Jesus did not need to remove the stone to go out from the tomb, but for us to enter the tomb. Do we still love Jesus even when we only see emptiness? Are we still faithful even if we did not find the Lord?
Yes, we believe in Jesus, and yes, we love Him. Yet, faith, hope and love are not static, but rather something that grows. God allows us to experience crosses and even empty tombs because, through these events, we may grow in our faith and love. We must not forget that when we carry a cross, we may be like Simon of Cyrene, who carried the cross of Jesus. We must not forget that Jesus was few steps away from the empty tomb, waiting to bless us.
Celebration of Easter is not just a annual ritual, with different fancies symbols, but an invitation for us to renew and deepen our faith and love for God. Afterall, Jesus is everything to us. Blessed Easter!
Valentinus Bayuhadi Ruseno, OP