Renungan pada Hari Minggu ke-31 dalam Masa Biasa [4 November 2018] Markus 12: 28-31
“Kamu harus mengasihi Tuhan, Tuhanmu… Yang kedua adalah ini: ‘Kamu harus mencintai sesamamu seperti dirimu sendiri.’ Tidak ada perintah lain yang lebih besar dari ini. “(Mrk. 12: 30-31)
 Hari-hari ini, saya sedang mempersiapkan tahbisan diakonat saya. Diakon sendiri adalah tahap transisi sebelum saya menjadi seorang imam. Terlepas dari kenyataan bahwa diakonat adalah masa transisi, seorang Diakon itu sendiri adalah masa hidup yang penting dalam kehidupan Gereja. Uskup Virgilio David, DD dari Kalookan, Metro Manila, mengingatkan 15 diakon Yesuit yang baru saja ditahbiskan Oktober lalu bahwa kita jangan melihat Diakon hanya sebagai langkah pertama menuju tingkat yang lebih tinggi, seperti imam dan uskup. Diakon adalah inti dalam lapisan lingkaran konsentris yang membentuk pelayanan tertahbis di Gereja. Diakon menjadi inti dari lingkaran pelayanan ini dan tanpa inti ini, para imam dan uskup akan runtuh. Ini adalah fondasi tempat kita membangun kepemimpinan di Gereja. Namun, mengapa Diakon harus ditempatkan sebagai inti dan menjadi fondasi?
Hari-hari ini, saya sedang mempersiapkan tahbisan diakonat saya. Diakon sendiri adalah tahap transisi sebelum saya menjadi seorang imam. Terlepas dari kenyataan bahwa diakonat adalah masa transisi, seorang Diakon itu sendiri adalah masa hidup yang penting dalam kehidupan Gereja. Uskup Virgilio David, DD dari Kalookan, Metro Manila, mengingatkan 15 diakon Yesuit yang baru saja ditahbiskan Oktober lalu bahwa kita jangan melihat Diakon hanya sebagai langkah pertama menuju tingkat yang lebih tinggi, seperti imam dan uskup. Diakon adalah inti dalam lapisan lingkaran konsentris yang membentuk pelayanan tertahbis di Gereja. Diakon menjadi inti dari lingkaran pelayanan ini dan tanpa inti ini, para imam dan uskup akan runtuh. Ini adalah fondasi tempat kita membangun kepemimpinan di Gereja. Namun, mengapa Diakon harus ditempatkan sebagai inti dan menjadi fondasi?
Paus Benediktus XVI dalam surat apostoliknya “Omnium in Mentem” memperjelas lebih lanjut identitas dasar seorang Diakon. Dia menulis, “Diakon diberdayakan untuk melayani umat Allah dalam pelayanan liturgi, sabda, dan kasih.” Para diakon adalah hati dari semua pelayan Gereja baik yang ditahbiskan maupun yang tidak ditahbiskan karena diakon melakukan dan mengingatkan kita akan tugas paling dasar dari setiap pelayan Gereja: untuk melayani dan mengasihi Allah dan umat-Nya. Kata Diakon berasal dari kata Yunani, “diakoneo” yang berarti melayani, dan karena itu, Diakon adalah seorang pelayan. Jika kita kembali ke bab pertama Injil Markus, orang pertama yang melayani Yesus, Sang Allah yang menjadi manusia, adalah ibu mertua Petrus (Mar 1:31). Dia melayani Yesus karena dia telah dipulihkan dari sakit. Ini bukan pelayanan yang dilakukan karena takut atau kebutuhan egois semata, tetapi atas syukur dan cinta kasih. Jadi, melayani dan mengasihi berada pada inti kehidupan seorang Diakon.
Dalam Injil hari ini, Yesus bertemu dengan seorang ahli Hukum Taurat yang bertanya tentang hukum yang paling utama. Dalam Hukum Taurat Musa, selain dari Sepuluh Perintah Allah, bangsa Yahudi memiliki ratusan lebih peraturan. Yesus menjawab, “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.” Yesus mengutip bagian dari Shema atau Kredo dasar Yahudi yang setiap orang Yahudi daraskan setiap hari (lihat Deu 6: 4-5). Namun, Yesus tidak berhenti sampai di situ saja. Dia melengkapi hukum pertama dan terbesar dengan hukum kedua, “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.” Ini juga berasal dari Perjanjian Lama (lihat Im 19:18). Sesungguhnya, jawaban Yesus pada dasarnya adalah ajaran yang ortodoks bagi orang Yahudi yang mendengar. Namun ada juga sesuatu yang baru.
Hubungan antara hukum pertama dan kedua menjadi kunci ajaran Yesus. Bagi Yesus, cinta kasih sejati kepada Tuhan harus diwujudnyatakan dalam cinta kasih kepada sesama, dan cinta sejati kepada sesama harus berorientasi kepada Tuhan. Jadi, sungguh tidak terpikirkan jika Yesus memerintahkan murid-murid-Nya untuk membunuh demi cinta akan Allah. Atau, Yesus tidak akan senang jika para pengikutnya hanya sibuk melakukan peribadatan, namun buta dengan ketidakadilan yang terjadi di dalam komunitas mereka.
Dengan mengingat hukum cinta kasih Yesus ini, kita sekarang dapat melihat mengapa peran diakon merupakan hal mendasar dalam Gereja. Diakon adalah mereka yang dipanggil dan diberdayakan untuk memenuhi hukum kasih Yesus. Diakon melayani dan mengasihi Allah dan umat-Nya, baik dalam konteks ibadah dan kehidupan sehari-hari. Meskipun benar bahwa diakon adalah salah satu pelayan yang ditahbiskan di Gereja, setiap pengikut Kristus juga dipanggil untuk menjadi “Diakon,” untuk melayani Allah dan umat-Nya berdasarkan cinta kasih. Tanpa hati seorang Diakon, yang merupakan inti dari pelayanan Gereja, setiap orang Kristiani, baik awam ataupun klerus, akan kehilangan identitas dan gagal untuk memenuhi hukum Kristus paling mendasar, hukum cinta kasih.
Frater Valentinus Bayuhadi Ruseno, OP


 I made my religious vow more than eight years ago with 12 other Dominican brothers. One of the most touching moments within this rite of the religious profession was when Fr. Provincial asked us, “What do you seek?” and we all prostrated, kiss the ground, and declared, “God’s mercy and yours!” After a brief moment, Fr. Provincial asked us to stand, and we began professing our vows before him. As I recall this defining moment in my life, I am pondering in my heart, “Why it has to be mercy?” Why do we not choose other Christian virtues? Why not fortitude, one of the cardinal virtues in the Christian tradition? Why not love, the greatest of all virtues?
I made my religious vow more than eight years ago with 12 other Dominican brothers. One of the most touching moments within this rite of the religious profession was when Fr. Provincial asked us, “What do you seek?” and we all prostrated, kiss the ground, and declared, “God’s mercy and yours!” After a brief moment, Fr. Provincial asked us to stand, and we began professing our vows before him. As I recall this defining moment in my life, I am pondering in my heart, “Why it has to be mercy?” Why do we not choose other Christian virtues? Why not fortitude, one of the cardinal virtues in the Christian tradition? Why not love, the greatest of all virtues? Saya mengucapkan kaul lebih dari delapan tahun yang lalu bersama dengan 12 frater lainnya. Salah satu momen paling menyentuh dalam ritual profesi religius ini adalah ketika Romo Provinsial bertanya kepada kami, “Apa yang kamu cari?” Dan kami semua bersujud dan berbaring di lantai, sambil berseru, “Belas kasih Tuhan dan juga komunitas!” Setelah beberapa saat, Pastor Provinsi meminta kami untuk berdiri, dan kami mulai mengucapkan kaul kami di hadapannya. Saat saya mengingat momen yang penting ini, saya merenungkan dalam hati saya, “Mengapa harus meminta belas kasih?” Mengapa kita tidak memilih keutamaan lainnya? Mengapa tidak keadilan, yang adalah salah satu keutamaan penting dalam tradisi Kristiani? Mengapa tidak cinta kasih, yang adalah keutamaan terbesar dari semua keutamaan?
Saya mengucapkan kaul lebih dari delapan tahun yang lalu bersama dengan 12 frater lainnya. Salah satu momen paling menyentuh dalam ritual profesi religius ini adalah ketika Romo Provinsial bertanya kepada kami, “Apa yang kamu cari?” Dan kami semua bersujud dan berbaring di lantai, sambil berseru, “Belas kasih Tuhan dan juga komunitas!” Setelah beberapa saat, Pastor Provinsi meminta kami untuk berdiri, dan kami mulai mengucapkan kaul kami di hadapannya. Saat saya mengingat momen yang penting ini, saya merenungkan dalam hati saya, “Mengapa harus meminta belas kasih?” Mengapa kita tidak memilih keutamaan lainnya? Mengapa tidak keadilan, yang adalah salah satu keutamaan penting dalam tradisi Kristiani? Mengapa tidak cinta kasih, yang adalah keutamaan terbesar dari semua keutamaan? “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” This familiar adage comes from an English noble, Lord Acton in his letter to Bishop Mandell Creighton in 1887. Lord Acton observed that people who possessed absolute control over other persons were inclined to abuse their power and exploit their subjects. This happens throughout human history. Jesus and His disciples themselves witnessed these corrupt powerful leaders during their time and eventually, became victims of this corruption.
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” This familiar adage comes from an English noble, Lord Acton in his letter to Bishop Mandell Creighton in 1887. Lord Acton observed that people who possessed absolute control over other persons were inclined to abuse their power and exploit their subjects. This happens throughout human history. Jesus and His disciples themselves witnessed these corrupt powerful leaders during their time and eventually, became victims of this corruption. “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Pepatah ini berasal dari bangsawan Inggris, Lord Acton dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton pada 1887. Lord Acton mengamati bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan mutlak atas orang lain cenderung menyalahgunakan kekuasaan mereka dan mengeksploitasi bawahan mereka. Ini terjadi sepanjang sejarah manusia. Yesus dan murid-murid-Nya sendiri menyaksikan para pemimpin korup ini pada zaman mereka dan akhirnya, menjadi korban kekuasaan yang korup tersebut.
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Pepatah ini berasal dari bangsawan Inggris, Lord Acton dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton pada 1887. Lord Acton mengamati bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan mutlak atas orang lain cenderung menyalahgunakan kekuasaan mereka dan mengeksploitasi bawahan mereka. Ini terjadi sepanjang sejarah manusia. Yesus dan murid-murid-Nya sendiri menyaksikan para pemimpin korup ini pada zaman mereka dan akhirnya, menjadi korban kekuasaan yang korup tersebut.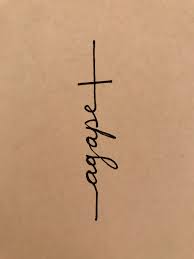 We discover at least three instances in the Bible in which Jesus explicitly expresses that He loves someone. The first instance is that Jesus loves the young rich man who seeks the eternal life (Mrk 10:21). The second is Jesus loves Martha, Mary, and Lazarus (Jn 11:5). The third is Jesus’ love for His disciples, especially His beloved disciple (Jn 13:34).
We discover at least three instances in the Bible in which Jesus explicitly expresses that He loves someone. The first instance is that Jesus loves the young rich man who seeks the eternal life (Mrk 10:21). The second is Jesus loves Martha, Mary, and Lazarus (Jn 11:5). The third is Jesus’ love for His disciples, especially His beloved disciple (Jn 13:34). Kita menemukan setidaknya tiga episode dalam Alkitab di mana Yesus secara eksplisit menyatakan bahwa Dia mengasihi seseorang. Yang pertama adalah Yesus yang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus (Yohanes 11: 5). Yang kedua adalah kasih Yesus bagi murid-murid-Nya (Yohanes 13:34). Yang ketiga dan menjadi fokus kita hari ini adalah Yesus yang mengasihi orang muda kaya yang mencari kehidupan kekal (Mrk 10:21).
Kita menemukan setidaknya tiga episode dalam Alkitab di mana Yesus secara eksplisit menyatakan bahwa Dia mengasihi seseorang. Yang pertama adalah Yesus yang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus (Yohanes 11: 5). Yang kedua adalah kasih Yesus bagi murid-murid-Nya (Yohanes 13:34). Yang ketiga dan menjadi fokus kita hari ini adalah Yesus yang mengasihi orang muda kaya yang mencari kehidupan kekal (Mrk 10:21). If there is one prayer that can change the course of world history, it is the earnest recitation of the holy rosary. In 1571, through the unceasing prayer of the rosary, a league of Christian nations called by Pope Pius V was able to stop the military advancement of the mighty Ottoman empire to western Europe in the Gulf of Patras, near Lepanto, Greece. In 1917, Our Lady appeared to three little children in Fatima, and one of her messages was to pray the rosary for the peace of the world. Through nation-wide recitation of the rosary, Austria was freed from the communist regime in 1955. In 1960, led by Catholic women marching the streets while praying the rosary, Brazil was also spared from communism.
If there is one prayer that can change the course of world history, it is the earnest recitation of the holy rosary. In 1571, through the unceasing prayer of the rosary, a league of Christian nations called by Pope Pius V was able to stop the military advancement of the mighty Ottoman empire to western Europe in the Gulf of Patras, near Lepanto, Greece. In 1917, Our Lady appeared to three little children in Fatima, and one of her messages was to pray the rosary for the peace of the world. Through nation-wide recitation of the rosary, Austria was freed from the communist regime in 1955. In 1960, led by Catholic women marching the streets while praying the rosary, Brazil was also spared from communism. When I was assigned to the hospital to serve as a chaplain, I witnessed the rise of diabetic cases as well as its terrifying effects on the patients. In simple term, diabetes is a condition in a person who can no longer naturally manage their blood sugar. In more serious cases, the body loses its natural ability to heal its wounds. In the beginning, it was a small open wound, yet since the body no longer heals, the infections set in, and this leads into gangrene or the death of the body’s tissues. I accompanied some patients who were struggling with this situation and witnessed how their fingers or even foot were darkened and deformed. When the ordinary treatment no longer worked, the amputation became the only merciful option as to prevent the spread of infections. As a chaplain, accompanying these patients was one of my toughest missions in the hospital.
When I was assigned to the hospital to serve as a chaplain, I witnessed the rise of diabetic cases as well as its terrifying effects on the patients. In simple term, diabetes is a condition in a person who can no longer naturally manage their blood sugar. In more serious cases, the body loses its natural ability to heal its wounds. In the beginning, it was a small open wound, yet since the body no longer heals, the infections set in, and this leads into gangrene or the death of the body’s tissues. I accompanied some patients who were struggling with this situation and witnessed how their fingers or even foot were darkened and deformed. When the ordinary treatment no longer worked, the amputation became the only merciful option as to prevent the spread of infections. As a chaplain, accompanying these patients was one of my toughest missions in the hospital. Ketika saya bertugas pelayanan di rumah sakit di Manila, saya menyadari bahwa kasus diabetes berkembang secara pesat, dan juga efeknya yang menakutkan bagi para pasien. Secara sederhana, diabetes adalah suatu kondisi pada seseorang yang tidak lagi dapat secara alami mengelola gula darahnya. Dalam kasus yang lebih serius, tubuh kehilangan kemampuan alami untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada awalnya adalah luka yang kecil, namun karena tubuh tidak lagi bisa meyembuhkan, infeksi-infeksi pun berkembang, dan ini mengarah pada gangren atau kematian jaringan-jaringan tubuh. Saya menemani beberapa pasien yang bergulat dengan situasi ini, dan menyaksikan bagaimana jari atau bahkan kaki mereka menghitam dan berubah bentuk. Ketika pengobatan biasa tidak lagi bekerja, amputasi menjadi satu-satunya pilihan untuk mencegah penyebaran infeksi. Sebagai seorang frater yang bertugas di rumah sakit, mendampingi pasien-pasien ini adalah salah satu misi terberat saya di rumah sakit.
Ketika saya bertugas pelayanan di rumah sakit di Manila, saya menyadari bahwa kasus diabetes berkembang secara pesat, dan juga efeknya yang menakutkan bagi para pasien. Secara sederhana, diabetes adalah suatu kondisi pada seseorang yang tidak lagi dapat secara alami mengelola gula darahnya. Dalam kasus yang lebih serius, tubuh kehilangan kemampuan alami untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada awalnya adalah luka yang kecil, namun karena tubuh tidak lagi bisa meyembuhkan, infeksi-infeksi pun berkembang, dan ini mengarah pada gangren atau kematian jaringan-jaringan tubuh. Saya menemani beberapa pasien yang bergulat dengan situasi ini, dan menyaksikan bagaimana jari atau bahkan kaki mereka menghitam dan berubah bentuk. Ketika pengobatan biasa tidak lagi bekerja, amputasi menjadi satu-satunya pilihan untuk mencegah penyebaran infeksi. Sebagai seorang frater yang bertugas di rumah sakit, mendampingi pasien-pasien ini adalah salah satu misi terberat saya di rumah sakit.