Minggu Pentakosta [9 Juni 2019] Yohanes 20: 19-23
 Hari ini kita merayakan hari raya Pentakosta, hari raya Roh Kudus yang datang dalam bentuk lidah api dan memenuhi hati para murid. Pertanyaannya yang bisa kita angkat adalah: Mengapa kita menyebut hari ini sebagai Pentakosta? Mengapa Roh Kudus datang hanya 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematian?
Hari ini kita merayakan hari raya Pentakosta, hari raya Roh Kudus yang datang dalam bentuk lidah api dan memenuhi hati para murid. Pertanyaannya yang bisa kita angkat adalah: Mengapa kita menyebut hari ini sebagai Pentakosta? Mengapa Roh Kudus datang hanya 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematian?
Iman kita bukan hanya ketaatan yang buta dan bodoh, tetapi iman yang mencari pengertian. Pencarian kita akan jawaban membawa kita kembali ke Perjanjian Lama. Dalam tradisi dan sejarah Yahudi, hari raya Pentakosta atau juga dikenal sebagai hari Tujuh Minggu adalah hari di mana mereka merayakan pemberian Hukum Taurat di Sinai. Lima puluh hari setelah hari Sabat Paskah Yahudi, orang-orang Israel berkumpul dan merayakan hari raya Pentakosta. Dalam Kitab Keluaran, kita akan menemukan bahwa sehari setelah tujuh minggu dari eksodus dari Mesir, Tuhan Allah menampakkan diri di Gunung Sinai, membuat perjanjian dengan Israel dan memberi mereka Hukum Taurat untuk mengatur umat-Nya. Jika Paskah Yahudi memperingati pembebasan mereka, hari raya Tujuh Minggu menunjuk pada hari Tuhan memberikan Hukum-Nya kepada Musa dan Israel di Sinai. Jadi, jika lima puluh hari setelah eksodus dari Mesir, orang Israel menerima Hukum Musa, para murid Yesus, lima puluh hari sejak hari kebangkitan menerima Roh Kudus, Hukum Kristus yang baru, yang tertulis dalam hati dan jiwa kita.
Untuk memahami Pentakosta, kita perlu memahami aspek formatif Hukum. Ketika Tuhan memberikan perjanjian dengan bangsa Israel, Dia menuntut mereka berperilaku seperti umat-Nya dan tidak mengikuti contoh bangsa-bangsa sekitar mereka. Untuk memfasilitasi ini, Allah memberi Israel seperangkat Hukum untuk dipatuhi. Sejatinya, Hukum Taurat adalah untuk membentuk bangsa Israel sebagai umat Allah. Dengan mengingat hal ini, kita sekarang dapat melihat pentingnya Pentakosta bagi para murid Yesus. Roh Kudus turun ke atas dan berdiam di dalam para murid sebagai Hukum Baru, dan sebagaimana Hukum Lama membentuk bangsa Israel yang lama, Hukum Baru adalah untuk membangun Israel Baru, yakni Gereja. Itulah sebabnya Pentakosta juga sebagai hari Gereja terbentuk atau hari lahir Gereja.
Menerima Roh Kudus di dalam hati kita adalah hak istimewa yang sangat besar, namun ini juga berarti kita juga harus hidup dalam Roh. Jika Israel kuno menyebut diri mereka sebagai umat Allah karena mereka mematuhi Hukum, maka kita dapat mengenali diri kita sendiri sebagai Umat Allah ketika kita mengikuti Roh. Namun, hidup dalam Roh bukanlah sekedar tentang bahasa roh atau bergabung dengan kelompok-kelompok Karismatik. St. Paulus dengan jelas menyatakan untuk hidup dalam Roh berlawanan dengan desakan kedagingan kita. Ketika kita melepaskan diri dari perbuatan kedagingan seperti amoralitas, penyembahan berhala, kebencian, perpecahan, kemarahan dan kecemburuan [Gal 5:19], kita sudah berjalan dalam Roh, dan ini bahkan lebih sulit daripada berbicara dalam bahasa roh. Roh Kudus telah memberikan kepada kita tujuh karunia-Nya, tetapi apakah kita berusaha untuk menjadi bijaksana, pengertian, saleh, tekun, berpengetahuan dalam iman, takut untuk menyinggung Tuhan [lihat Yesaya 11: 1]? Ini akan menjadi kehilangan terbesar kita jika kita merayakan Pentakosta, namun kita hidup seolah-olah kita tidak pernah menerima Roh Kudus.
Diakon Valentinus Bayuhadi Ruseno, OP


 If you are a fan of Marvel universe movies, you will easily remember Thanos, the primary villain with twisted moral conviction. After he swept half of the living beings in the universe with the power of the infinity stones, he went into hiding. Yet, the Avenger found him and forced him to restore the world, but he said it was no longer possible because he has destroyed the stones, because what he did was inevitable, and he said, “I am inevitable”.
If you are a fan of Marvel universe movies, you will easily remember Thanos, the primary villain with twisted moral conviction. After he swept half of the living beings in the universe with the power of the infinity stones, he went into hiding. Yet, the Avenger found him and forced him to restore the world, but he said it was no longer possible because he has destroyed the stones, because what he did was inevitable, and he said, “I am inevitable”. Ada tiga respons terhadap kesulitan dalam hidup. Yang pertama adalah menghindari atau melarikan diri. Yang kedua adalah menyerah pasrah. Yang terakhir adalah merangkul dan mengubahnya menjadi sarana pertumbuhan dan kemuliaan kita. Ini adalah kemuliaan yang tidak murahan karena mengalir dari kesulitan, kerja keras dan pengorbanan. Ini adalah kemulian sejati karena tidak bisa dibeli dengan uang tetapi diperoleh dari kucuran keringat, air mata dan bahkan darah.
Ada tiga respons terhadap kesulitan dalam hidup. Yang pertama adalah menghindari atau melarikan diri. Yang kedua adalah menyerah pasrah. Yang terakhir adalah merangkul dan mengubahnya menjadi sarana pertumbuhan dan kemuliaan kita. Ini adalah kemuliaan yang tidak murahan karena mengalir dari kesulitan, kerja keras dan pengorbanan. Ini adalah kemulian sejati karena tidak bisa dibeli dengan uang tetapi diperoleh dari kucuran keringat, air mata dan bahkan darah.
 One of the greatest gifts to humanity is the gift of memory. It gives us a sense of identity. Biology teaches us that almost all our body parts are being replaced over the years. One-year-old Stephen is biologically different from thirty-year-old Stephen. All bodily cells, with the sole exception of his eyes’ lens, are changed. What unites thirty-year-old Stephen with his younger self as well as his future self is his memory.
One of the greatest gifts to humanity is the gift of memory. It gives us a sense of identity. Biology teaches us that almost all our body parts are being replaced over the years. One-year-old Stephen is biologically different from thirty-year-old Stephen. All bodily cells, with the sole exception of his eyes’ lens, are changed. What unites thirty-year-old Stephen with his younger self as well as his future self is his memory. Salah satu karunia terbesar bagi umat manusia adalah memori. Ini memberi kesadaran akan identitas kita. Biologi mengajarkan kita bahwa hampir semua bagian tubuh kita akan tergantikan saat kita hidup. Stephen yang berusia satu tahun secara biologis berbeda dari Stephen yang berusia tiga puluh tahun. Semua sel tubuhnya telah digantikan dan akan terus digantikan sampai ia wafat. Apa yang menyatukan Stephen yang berusia tiga puluh tahun dengan dirinya yang lebih muda serta diri di masa depannya adalah ingatannya.
Salah satu karunia terbesar bagi umat manusia adalah memori. Ini memberi kesadaran akan identitas kita. Biologi mengajarkan kita bahwa hampir semua bagian tubuh kita akan tergantikan saat kita hidup. Stephen yang berusia satu tahun secara biologis berbeda dari Stephen yang berusia tiga puluh tahun. Semua sel tubuhnya telah digantikan dan akan terus digantikan sampai ia wafat. Apa yang menyatukan Stephen yang berusia tiga puluh tahun dengan dirinya yang lebih muda serta diri di masa depannya adalah ingatannya. “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” This familiar adage comes from an English noble, Lord Acton in his letter to Bishop Mandell Creighton in 1887. Lord Acton observed that people who possessed absolute control over other persons were inclined to abuse their power and exploit their subjects. This happens throughout human history. Jesus and His disciples themselves witnessed these corrupt powerful leaders during their time and eventually, became victims of this corruption.
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” This familiar adage comes from an English noble, Lord Acton in his letter to Bishop Mandell Creighton in 1887. Lord Acton observed that people who possessed absolute control over other persons were inclined to abuse their power and exploit their subjects. This happens throughout human history. Jesus and His disciples themselves witnessed these corrupt powerful leaders during their time and eventually, became victims of this corruption. “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Pepatah ini berasal dari bangsawan Inggris, Lord Acton dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton pada 1887. Lord Acton mengamati bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan mutlak atas orang lain cenderung menyalahgunakan kekuasaan mereka dan mengeksploitasi bawahan mereka. Ini terjadi sepanjang sejarah manusia. Yesus dan murid-murid-Nya sendiri menyaksikan para pemimpin korup ini pada zaman mereka dan akhirnya, menjadi korban kekuasaan yang korup tersebut.
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Pepatah ini berasal dari bangsawan Inggris, Lord Acton dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton pada 1887. Lord Acton mengamati bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan mutlak atas orang lain cenderung menyalahgunakan kekuasaan mereka dan mengeksploitasi bawahan mereka. Ini terjadi sepanjang sejarah manusia. Yesus dan murid-murid-Nya sendiri menyaksikan para pemimpin korup ini pada zaman mereka dan akhirnya, menjadi korban kekuasaan yang korup tersebut.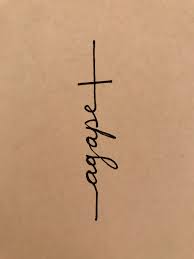 We discover at least three instances in the Bible in which Jesus explicitly expresses that He loves someone. The first instance is that Jesus loves the young rich man who seeks the eternal life (Mrk 10:21). The second is Jesus loves Martha, Mary, and Lazarus (Jn 11:5). The third is Jesus’ love for His disciples, especially His beloved disciple (Jn 13:34).
We discover at least three instances in the Bible in which Jesus explicitly expresses that He loves someone. The first instance is that Jesus loves the young rich man who seeks the eternal life (Mrk 10:21). The second is Jesus loves Martha, Mary, and Lazarus (Jn 11:5). The third is Jesus’ love for His disciples, especially His beloved disciple (Jn 13:34). Kita menemukan setidaknya tiga episode dalam Alkitab di mana Yesus secara eksplisit menyatakan bahwa Dia mengasihi seseorang. Yang pertama adalah Yesus yang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus (Yohanes 11: 5). Yang kedua adalah kasih Yesus bagi murid-murid-Nya (Yohanes 13:34). Yang ketiga dan menjadi fokus kita hari ini adalah Yesus yang mengasihi orang muda kaya yang mencari kehidupan kekal (Mrk 10:21).
Kita menemukan setidaknya tiga episode dalam Alkitab di mana Yesus secara eksplisit menyatakan bahwa Dia mengasihi seseorang. Yang pertama adalah Yesus yang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus (Yohanes 11: 5). Yang kedua adalah kasih Yesus bagi murid-murid-Nya (Yohanes 13:34). Yang ketiga dan menjadi fokus kita hari ini adalah Yesus yang mengasihi orang muda kaya yang mencari kehidupan kekal (Mrk 10:21).