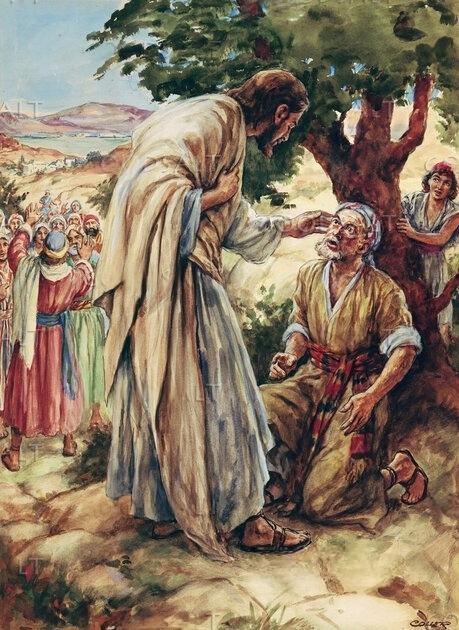Hari Minggu ke-24 dalam Masa Biasa [B]
15 September 2024
Yakobus 2:14-18
Ketika Martin Luther memisahkan diri dari Gereja Katolik, ia mulai menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa asli Jerman. Namun, ia tidak hanya menerjemahkan tetapi juga memilah-milah kitab-kitab dalam Alkitab. Dia menempatkan beberapa kitab di bagian lampiran, bukan di tempat biasanya, dan salah satunya adalah Surat Yakobus. Ia menjuluki surat tersebut sebagai ‘surat jerami’. Untungnya, orang-orang Kristen pada umumnya tidak mengikuti rekomendasi Luther ini, dan tetap melihat surat itu sebagai kanonik atau bagian dari Kitab Suci. Pertanyaannya: mengapa Luther ingin menghapus surat ini dari Alkitab?

Alasan Luther melihat surat St. Yakobus sebagai ‘jerami’ atau tidak berguna adalah karena surat tersebut tidak sesuai dengan teologinya atau pemikirannya. Dalam kata pengantar untuk terjemahan Perjanjian Baru yang dibuatnya pada tahun 1522, ia berkomentar bahwa surat tersebut ‘tidak memiliki sifat Injili sama sekali’. Ia menilai bahwa surat tersebut bertentangan dengan keyakinannya akan keselamatan hanya melalui iman (dalam bahasa Latin, sola fide). Salah satu ayat yang menentang ide sola fide adalah Yakobus 2:24. “Kamu tahu, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman.”
Untuk memahami lebih jauh apa yang dimaksud oleh ayat ini, pertama-tama kita harus memahami ‘sola fide’. Martin Luther percaya bahwa manusia dibenarkan di hadapan Allah hanya karena iman. Ketika kita berdosa, bagi Luther, kodrat kita benar-benar hancur, dan kita ditakdirkan untuk masuk neraka. Namun, pengorbanan Yesus di salib menyembunyikan kodrat kita yang rusak ini, dan kita dibenarkan karena Allah tidak melihat kita, tetapi Yesus di salib yang menutupi kebobrokan kita. Yang perlu kita lakukan adalah memiliki iman atau percaya kepada janji keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Luther menyangkal bahwa perbuatan yang kita lakukan, tidak peduli seberapa baik perbuatan itu, akan bermanfaat bagi pembenaran kita.
Sementara itu, Yakobus, saudara Tuhan kita dan juga uskup Yerusalem, menulis suratnya sekitar 1500 tahun sebelum Luther. Memang, ia tidak secara khusus menulis untuk menentang Luther, tetapi secara kebetulan, ia menulis untuk menentang mereka yang memiliki mentalitas seperti Luther. Selain membahas beberapa masalah dalam komunitasnya, seperti diskriminasi terhadap orang miskin, terutama dalam perayaan Ekaristi (2:1-6) dan pelanggaran Sepuluh Perintah Allah (2:6-13), Yakobus juga mengkritik beberapa orang yang mengklaim beriman kepada Yesus Kristus tetapi mengabaikan perbuatan cinta kasih. Iman yang didasarkan pada akal budi dan keyakinan tidaklah cukup untuk keselamatan. Yakobus mengajarkan bahwa iman yang menyelamatkan akan terwujud dalam kasih. Di sini, Yakobus sependapat dengan Santo Paulus yang mengatakan bahwa keselamatan terjadi melalui “iman yang bekerja oleh kasih” (Gal. 5:6).
Akhirnya, Yakobus juga mengajarkan apa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid-Nya. Dalam Injil hari ini, Yesus bertanya kepada murid-murid-Nya, “Siapakah Aku?” Simon Petrus dengan tepat menjawab, “Engkau adalah Kristus.” Namun, pengakuan iman Petrus mengandung kebenaran yang lebih mendasar. Yesus mengajarkan bahwa mereka harus memikul salib mereka untuk mengikuti Kristus. Iman kepada Yesus mensyaratkan salib kita, yaitu pengorbanan kasih. Tidaklah cukup membiarkan Yesus memikul salib-Nya sementara kita duduk manis dan menyaksikan pengorbanan-Nya. Kita juga perlu mengambil bagian dalam salib-Nya.
Surat Yakobus adalah pengingat untuk tidak memilih ayat-ayat Alkitab yang sesuai dengan teologi kita, melainkan untuk hidup sesuai dengan ajaran Yesus, yang diturunkan kepada para rasul.
Valentinus Bayuhadi Ruseno, OP
Pertanyaan-pertanyaan panduan:
Apakah kita beriman kepada Allah? Bagaimana kita memahami iman kita? Apakah kita menghidupi iman kita dalam karya kasih? Apa saja perbuatan kasih yang kita lakukan untuk mengekspresikan iman kita? Apakah kita mampu menjelaskan iman kita kepada orang-orang yang bertanya? Apakah kita membagikan iman kita? Bagaimanakah kita membagikan iman kita? Apakah orang-orang menjadi lebih dekat dengan Allah karena iman kita? Atau Apakah orang-orang menjauh dari Allah karena kita?