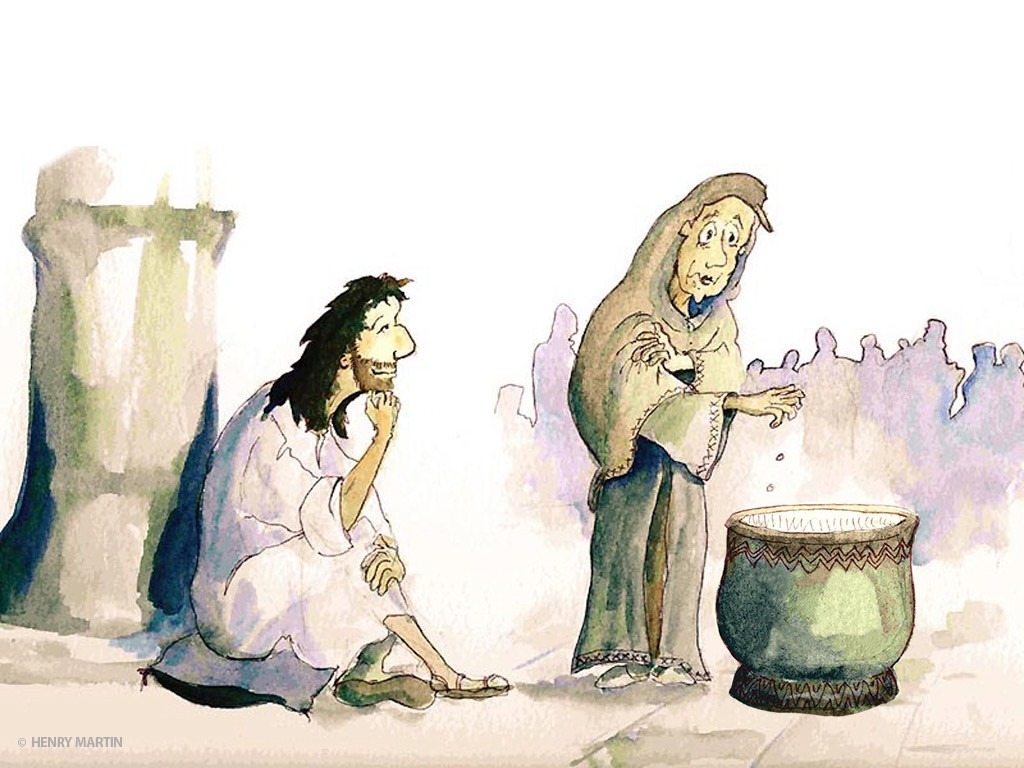Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam [B]
24 November 2024
Yohanes 18:33b-37
Di zaman sekarang, konsep raja mungkin terasa aneh dan bahkan ketinggalan zaman. Banyak dari kita hidup dalam masyarakat yang demokratis, di mana kita memilih orang-orang yang kita sukai untuk menjadi pemimpin kita, dan memilih yang lain ketika kita merasa bahwa mereka tidak lagi cocok untuk memimpin. Kemegahan dan keagungan kerajaan-istana, benteng, jubah, dan upacara-upacara kebangsawanan-sering kali dipandang sebagai peninggalan masa lalu. Namun, Gereja memanggil kita untuk merenungkan dan menerima Yesus sebagai Raja. Bagaimana kita dapat benar-benar menghargai identitas Yesus sebagai Raja kita?

Pertama, Yesus adalah raja yang melayani. Ya, Yesus adalah raja, tetapi tidak seperti raja-raja lainnya. Gabriel, sang malaikat agung, mengumumkan kelahiran-Nya sebagai raja, “Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan (Luk. 1:33).” Namun, Yesus menyatakan bagaimana Dia akan menjadi raja, “Karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Mar 10:45).” Alih-alih menuntut pelayanan dari umat-Nya, Yesus melayani umat-Nya dengan kerendahan hati yang luar biasa. Tindakan pelayanan-Nya yang paling utama adalah mengorbankan diri-Nya di kayu salib demi keselamatan kita. Bahkan sekarang, sebagai Raja yang telah bangkit di surga, Yesus terus melayani dengan menjadi pengantara kita di hadapan Bapa (Ibr. 7:25).
Kedua, Yesus, raja semesta. Meskipun Yesus dilahirkan sebagai seorang Yahudi dan dinubuatkan sebagai Mesias Israel, kekuasaan-Nya bersifat universal. Setelah kebangkitan-Nya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. (Matius 28:18)” Yesus bukan hanya raja atas semua manusia, tetapi juga atas segala sesuatu. Dari bintang terbesar hingga partikel sub-atom terkecil, dan bahkan realitas yang belum ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern, semuanya berada dalam pemerintahan dan penyelenggaraan-Nya. Tidak hanya realitas yang terlihat, tetapi juga makhluk-makhluk yang tidak terlihat juga berada di bawah kekuasaan Yesus. Kemudian, karena kerajaan Yesus adalah tentang pelayanan, maka Yesus juga melayani segala sesuatu dengan melestarikan keberadaan mereka, jika tidak, segala sesuatu akan runtuh menuju ketiadaan.
Ketiga, Yesus adalah Raja kita. Kerajaan Yesus tidaklah jauh atau abstrak, tetapi sangat personal. Sebagai Raja atas segala ciptaan, Dia mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita karena Dia mengenal dan mengasihi kita masing-masing. Desain alam semesta yang rumit, dari hukum fisika hingga kondisi yang disesuaikan dengan baik yang memungkinkan kehidupan di Bumi, mencerminkan perhatian-Nya yang penuh kasih. Bahkan tubuh kita sendiri, yang terdiri dari atom dan sel yang tak terhitung jumlahnya, disatukan di bawah perintah-Nya. Tidak hanya alam semesta yang terlihat, bahkan makhluk-makhluk spiritual pun berada di bawah perintah-Nya untuk melindungi dan menuntun kita menuju kebahagiaan sejati.
Sementara kita sering kali sibuk dengan urusan sehari-hari, sang Raja memelihara kita melalui pemerintahan-Nya atas seluruh alam semesta, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pemerintahan-Nya sebagai raja tidak lain adalah kasih, pelayanan dan perhatian.
Roma
Valentinus Bayuhadi Ruseno, OP
Pertanyaan-pertanyaan untuk refleksi:
Apa konsepmu tentang seorang raja? Apakah kamu melihat Yesus sebagai seorang raja? Raja yang seperti apa Dia itu? Atau, apakah kamu lebih nyaman dengan sebutan lain Yesus seperti gembala yang baik? Apakah kita mengikuti Yesus sebagai Raja kita? Bagaimana kita melayani Raja kita? Apakah kita menaati-Nya, atau kita memberontak terhadap-Nya? Apakah kita juga menjaga ciptaan lain karena mereka melayani Raja yang sama seperti kita? Apakah kita berterima kasih kepada para malaikat yang telah menjaga kita?