Minggu Paskah ke-6 [6 Mei 2018] Yohanes 15:9-17
 Kita hidup di belahan dunia dimana kekerasan dan kematian telah menjadi konsumsi sehari-hari kita. Setiap hari, kehidupan manusia secara paksa dirampas karena alasan yang sangat sepele. Orang tua membunuh bayi mereka. Saudara menghabisi saudara. Sahabat memanipulasi dan memanfaatkan sahabat. Beberapa dari kita mungkin turun ke jalan dan menuntut keadilan. Namun, banyak dari kita terlalu sibuk dengan kegiatan sehari-hari, karena kita harus bekerja, belajar dan menjalankan tugas-tugas lainnya. Kita menjadi mati rasa atau buta terhadap tanah yang telah menjadi merah oleh darah saudara-saudari kita. Kehidupan, berharga di mata Tuhan, ternyata sangat murah di tangan manusia.
Kita hidup di belahan dunia dimana kekerasan dan kematian telah menjadi konsumsi sehari-hari kita. Setiap hari, kehidupan manusia secara paksa dirampas karena alasan yang sangat sepele. Orang tua membunuh bayi mereka. Saudara menghabisi saudara. Sahabat memanipulasi dan memanfaatkan sahabat. Beberapa dari kita mungkin turun ke jalan dan menuntut keadilan. Namun, banyak dari kita terlalu sibuk dengan kegiatan sehari-hari, karena kita harus bekerja, belajar dan menjalankan tugas-tugas lainnya. Kita menjadi mati rasa atau buta terhadap tanah yang telah menjadi merah oleh darah saudara-saudari kita. Kehidupan, berharga di mata Tuhan, ternyata sangat murah di tangan manusia.
Namun, beberapa hari yang lalu, saya sangat terganggu oleh berita seorang imam muda yang dibunuh secara brutal. Namanya adalah Mark Antony Ventura, dan dia baru berusia 37 tahun ketika dia tanpa belas kasih ditembak mati. Hidupnya diambil beberapa saat setelah ia merayakan misa paginya di Cagayan, Filipina. Dia masih di dalam kapel kecil, sedang memberikan berkatnya kepada anak-anak, dan tiba-tiba, seorang pria tak dikenal datang dan menembaknya. Alasan kepada dia dihabisi belum jelas, namun advokasinya untuk keadilan dan kedamaian mungkin menjadi alasan utama.
Kematiannya mengingatkan akan kematian Uskup Agung Oscar Romero dari San Salvador. Uskup kudus ini dibunuh tepat setelah mengkonsekrasikan tubuh dan darah Kristus, dan saat dia jatuh ke tanah, darahnya bersatu dengan darah Kristus. Uskup lainnya, seorang Dominikan, Pierre Claverie, OP dari Oran, Aljazair mengalami nasib yang serupa. Para teroris meletakan bom di mobilnya, dan ledakannya tidak hanya membunuh Bishop Pierre, tetapi juga sahabat dan sopirnya yang beragama Islam. Dalam kejadian berdarah itu, dagingnya bersatu dengan daging teman Muslimnya.
Menyaksikan tubuh romo Mark yang terbaring tanpa nyawa di tanah dan bersimbah darah, tidak hanya sangat mengusik hati nurani, tetapi juga sangat menyakitkan. Hal ini sangat mengusik hati nurani karena memberi kita efek mengerikan bahwa jika orang-orang jahat ini bisa tanpa ampun membunuh seorang imam, duta pengampunan dan belas kasih, sekarang mereka bisa menghancurkan siapa saja yang menghalangi di jalan mereka. Namun, kematiannya juga menyakitkan karena kematiannya adalah juga kematian kita sebagai Umat Tuhan. Jubah putihnya yang bercampur tanah dan bersimbah darah, adalah pakaian putih kita yang kita kenakan saat kita dibaptis. Tangannya yang tidak lagi bernyawa, yang pernah memberkati orang-orang dan menguduskan roti dan anggur suci, adalah juga tangan kita yang membesarkan anak-anak kita dan membangun masyarakat. Mulutnya yang terbungkam yang pernah mewartakan Kabar Baik, mengampuni dosa, dan mengutuk kejahatan, adalah juga mulut kita yang menerima hosti kudus dan mengajarkan kebijaksanaan kepada anak-anak kita. Pembunuhan romo Markus adalah pembunuhan seorang imam, dan secara simbolis ini adalah pembunuhan kita semua, umat Allah.
Jalan imamat adalah jalan yang saya dan beberapa dari kita telah pilih. Ini adalah jalan yang sering memberi kita kenyamanan duniawi, dan bonus tak terduga. Ini adalah jalan yang menghujani kita dengan ketenaran, kesuksesan, dan kemuliaan. Namun, ini adalah jalan yang sama yang menghadapkan kita dengan wajah kejahatan. Ini adalah jalan yang yang menantang kita untuk berada di sisi para korban dan membela keadilan. Ini adalah jalan yang membuat kita dianiaya, diejek dan bahkan dibunuh. Pilihannya adalah milik kita. Untuk mengakhiri renungan kecil ini, izinkan saya mengutip Uskup Agung Oscar Romero, “Sebuah gereja yang tidak memprovokasi krisis apa pun, sebuah Injil yang tidak mengusik hati nurani, sebuah Firman Tuhan yang tidak ada masuk ke dalam jiwa siapa pun, sebuah Injil yang tidak berhadapan dengan dosa nyata dari masyarakat di mana Injil itu diwartakan – Injil macam apakah itu? ”
Br. Valentinus Bayuhadi Ruseno, OP




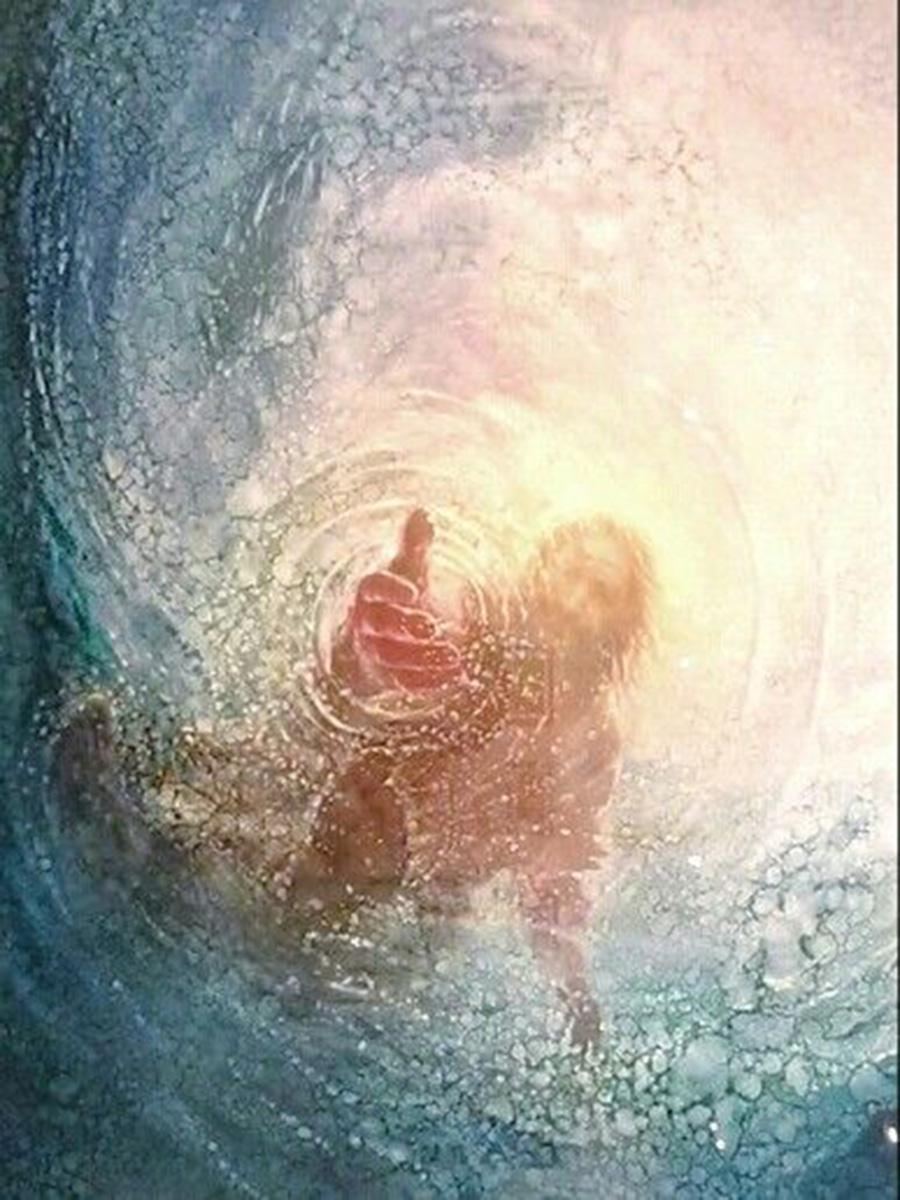
 Ocean is a gift to humanity. For many of us, ocean means a great variety of seafood, a place to spend our vacation. When we imagine a vast sea with beautiful beach, we are ready to enjoy swimming, snorkeling or diving. However, for millions of fishermen and seafarers, sea simply means life as they depend their lives and their families on the generosity of the sea, the resources it offers, and the works it generates. Unfortunately, the sea is not always merciful. The sea is home to powerful storms and with its giant waves that can even engulf the biggest of ships. With the effects of global warming, massive sea pollution and destructive ways of fishing, it is getting hard to get a good catch. Novelist Ernest Hemingway in his book “The Old Man and the Sea” narrates a life of fisherman who after risking his life to catch a giant fish, brings home nothing but a fishbone as his catch was consumed by other fishes. Majority of fishermen who continue struggling with lingering debt and difficulty to get fuel for their boats, become poorer by the day. These make fishermen and seafarers a perilous profession.
Ocean is a gift to humanity. For many of us, ocean means a great variety of seafood, a place to spend our vacation. When we imagine a vast sea with beautiful beach, we are ready to enjoy swimming, snorkeling or diving. However, for millions of fishermen and seafarers, sea simply means life as they depend their lives and their families on the generosity of the sea, the resources it offers, and the works it generates. Unfortunately, the sea is not always merciful. The sea is home to powerful storms and with its giant waves that can even engulf the biggest of ships. With the effects of global warming, massive sea pollution and destructive ways of fishing, it is getting hard to get a good catch. Novelist Ernest Hemingway in his book “The Old Man and the Sea” narrates a life of fisherman who after risking his life to catch a giant fish, brings home nothing but a fishbone as his catch was consumed by other fishes. Majority of fishermen who continue struggling with lingering debt and difficulty to get fuel for their boats, become poorer by the day. These make fishermen and seafarers a perilous profession.
 Laut adalah anugerah bagi umat manusia. Bagi banyak dari kita, laut berarti berbagai macam seafood, dan tempat untuk menikmati liburan. Bila kita membayangkan lautan luas dengan pantai yang indah, kita siap untuk berenang, snorkeling atau menyelam. Namun, ini jauh berbeda bagi jutaan nelayan dan pelaut. Laut berarti kehidupan karena mereka menggantungkan hidup mereka dan keluarga mereka pada laut, baik sumber daya yang dimiliki dan perkerjaan yang dihasilkan. Sayangnya, laut tidak selalu berarti kehidupan. Laut adalah tempat bagi badai-badai dahsyat dan gelombang-gelombang raksasa yang bahkan bisa menelan kapal-kapal terbesar yang pernah dibangun manusia. Dengan efek pemanasan global, polusi laut yang masif dan cara-cara penangkapan ikan yang merusak alam, sekarang semakin sulit bagi nelayan sederhana untuk mendapatkan tangkapan yang baik. Penulis Ernest Hemingway dalam bukunya “The Old Man and the Sea” menceritakan tentang kehidupan nelayan tua yang setelah mempertaruhkan nyawanya untuk menangkap ikan raksasa, tidak membawa pulang apapun kecuali tulang ikan karena tangkapannya dihabisi oleh ikan-ikan lain. Mayoritas para nelayan terus berjuang dengan hutang dan sulitnya mendapatkan bahan bakar untuk perahu mereka. Merekapun menjadi semakin miskin dari hari ke hari. Hal ini membuat nelayan dan pelaut adalah profesi yang berbahaya.
Laut adalah anugerah bagi umat manusia. Bagi banyak dari kita, laut berarti berbagai macam seafood, dan tempat untuk menikmati liburan. Bila kita membayangkan lautan luas dengan pantai yang indah, kita siap untuk berenang, snorkeling atau menyelam. Namun, ini jauh berbeda bagi jutaan nelayan dan pelaut. Laut berarti kehidupan karena mereka menggantungkan hidup mereka dan keluarga mereka pada laut, baik sumber daya yang dimiliki dan perkerjaan yang dihasilkan. Sayangnya, laut tidak selalu berarti kehidupan. Laut adalah tempat bagi badai-badai dahsyat dan gelombang-gelombang raksasa yang bahkan bisa menelan kapal-kapal terbesar yang pernah dibangun manusia. Dengan efek pemanasan global, polusi laut yang masif dan cara-cara penangkapan ikan yang merusak alam, sekarang semakin sulit bagi nelayan sederhana untuk mendapatkan tangkapan yang baik. Penulis Ernest Hemingway dalam bukunya “The Old Man and the Sea” menceritakan tentang kehidupan nelayan tua yang setelah mempertaruhkan nyawanya untuk menangkap ikan raksasa, tidak membawa pulang apapun kecuali tulang ikan karena tangkapannya dihabisi oleh ikan-ikan lain. Mayoritas para nelayan terus berjuang dengan hutang dan sulitnya mendapatkan bahan bakar untuk perahu mereka. Merekapun menjadi semakin miskin dari hari ke hari. Hal ini membuat nelayan dan pelaut adalah profesi yang berbahaya.
 Yoke is a device, usually of wood, placed on the shoulder of animals or persons to carry a burden. In agricultural settings, a yoke is used to pull a plow to make a furrow on the ground so that the soil will be ready for the seed planting. But, a yoke can be used also to drag a cart and transport various goods. Because its primary function is to carry a load or burden, a yoke turns to be a symbol of responsibility, hard work, and obligation. In our seminary in Manila, a leader among the brothers is called a decano. In the beginning of the formation year, we elect our decano, and as he assumes his responsibility, he ceremonially receives a wooden yoke from the outgoing decano. The yoke reminds him of responsibility and great task that he has to endure through the year.
Yoke is a device, usually of wood, placed on the shoulder of animals or persons to carry a burden. In agricultural settings, a yoke is used to pull a plow to make a furrow on the ground so that the soil will be ready for the seed planting. But, a yoke can be used also to drag a cart and transport various goods. Because its primary function is to carry a load or burden, a yoke turns to be a symbol of responsibility, hard work, and obligation. In our seminary in Manila, a leader among the brothers is called a decano. In the beginning of the formation year, we elect our decano, and as he assumes his responsibility, he ceremonially receives a wooden yoke from the outgoing decano. The yoke reminds him of responsibility and great task that he has to endure through the year.
 Kuk adalah sebuah alat, biasanya terbuat dari kayu, yang diletakkan di bahu hewan atau orang untuk membawa beban. Di lingkungan pertanian, kuk digunakan untuk menarik bajak untuk membuat alur di tanah sehingga tanah siap untuk penanaman benih. Tapi, kuk bisa digunakan juga untuk menarik gerobak dan mengangkut berbagai barang. Karena fungsi utamanya adalah untuk membawa beban, kuk pun menjadi simbol tanggung jawab, kerja keras, dan kewajiban. Di seminari kami di Manila, pemimpin di antara para frater disebut sebagai “dekano”. Pada awal tahun formasi, kami memilih dekano, dan saat dia memulai mengembang tanggung jawabnya, dia secara seremonial menerima kuk kayu dari dekano yang lama. Kuk itu mengingatkannya akan tanggung jawab dan tugas besar yang harus dia tanggung sepanjang tahun dalam memimpin komunitas para frater.
Kuk adalah sebuah alat, biasanya terbuat dari kayu, yang diletakkan di bahu hewan atau orang untuk membawa beban. Di lingkungan pertanian, kuk digunakan untuk menarik bajak untuk membuat alur di tanah sehingga tanah siap untuk penanaman benih. Tapi, kuk bisa digunakan juga untuk menarik gerobak dan mengangkut berbagai barang. Karena fungsi utamanya adalah untuk membawa beban, kuk pun menjadi simbol tanggung jawab, kerja keras, dan kewajiban. Di seminari kami di Manila, pemimpin di antara para frater disebut sebagai “dekano”. Pada awal tahun formasi, kami memilih dekano, dan saat dia memulai mengembang tanggung jawabnya, dia secara seremonial menerima kuk kayu dari dekano yang lama. Kuk itu mengingatkannya akan tanggung jawab dan tugas besar yang harus dia tanggung sepanjang tahun dalam memimpin komunitas para frater.
 Jesus was about to leave His disciples and go back to His Father. The disciples were confused and failed to understand. Some were afraid of losing their Messiah. Some were puzzled by the actions of Jesus. Yet, despite this confusion and fear, Jesus reminded them not be troubled and to have faith in God and in Him.
Jesus was about to leave His disciples and go back to His Father. The disciples were confused and failed to understand. Some were afraid of losing their Messiah. Some were puzzled by the actions of Jesus. Yet, despite this confusion and fear, Jesus reminded them not be troubled and to have faith in God and in Him.
 Yesus hendak meninggalkan murid-murid-Nya dan kembali kepada Bapa-Nya. Para murid bingung dan tidak mengerti. Beberapa takut kehilangan Mesias dan guru mereka. Beberapa tidak mengerti dengan tindakan dan perkataan Yesus. Namun, terlepas dari kebingungan dan ketakutan ini, Yesus mengingatkan mereka agar tidak merasa cemas dan tetap memiliki iman kepada Allah dan kepada-Nya.
Yesus hendak meninggalkan murid-murid-Nya dan kembali kepada Bapa-Nya. Para murid bingung dan tidak mengerti. Beberapa takut kehilangan Mesias dan guru mereka. Beberapa tidak mengerti dengan tindakan dan perkataan Yesus. Namun, terlepas dari kebingungan dan ketakutan ini, Yesus mengingatkan mereka agar tidak merasa cemas dan tetap memiliki iman kepada Allah dan kepada-Nya.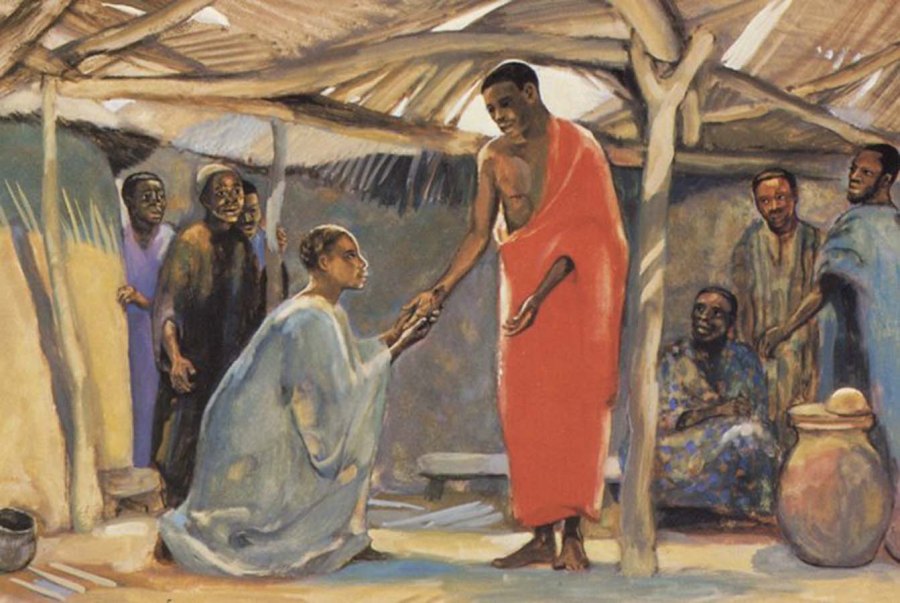
 Thomas was looking for a proof that Jesus truly rose from the dead. Not only seeing Him in person, he required another sign: touching the crucifixion marks that Jesus bore. He was one of the Twelve, the inner cycle of Jesus’ disciples, and being one, he had the privilege to walk with Jesus, dine with Him, and witness His mighty deeds. At a first glance, he would easily recognize Jesus, his Master, but still, he demanded the marks of the nails. Why did Thomas insist on searching the wounds?
Thomas was looking for a proof that Jesus truly rose from the dead. Not only seeing Him in person, he required another sign: touching the crucifixion marks that Jesus bore. He was one of the Twelve, the inner cycle of Jesus’ disciples, and being one, he had the privilege to walk with Jesus, dine with Him, and witness His mighty deeds. At a first glance, he would easily recognize Jesus, his Master, but still, he demanded the marks of the nails. Why did Thomas insist on searching the wounds?