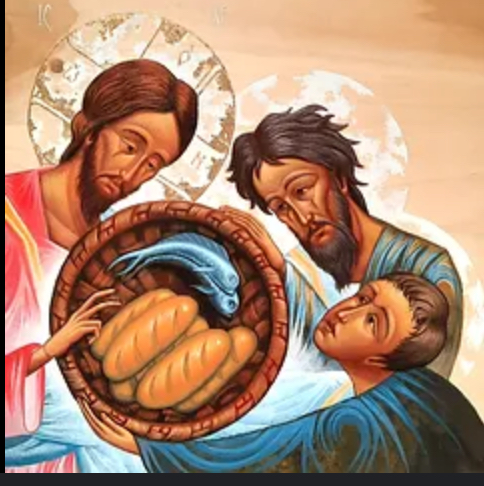The Assumption of the Blessed Virgin Mary
August 15, 2024 [B]
Luke 1:39-56
Today, the Church is celebrating the great feast of the Assumption of our Blessed Virgin Mary. Through this celebration, the Church reminds us that Mary, the mother of our Lord, when the course of her life ended, was assumed both her soul and body into the heavenly glory. Yet, a question may arise: why did Mary have to go up into heaven with her soul and body immediately after her death, while the rest of us must wait until the final judgment? Is it unfair?

The reason is love. St. Thomas Aquinas teaches that love seeks the union with the beloved (see ST. I.II. q.28 a.1). In a simple way, when we love someone, we wish that we are always close to that person, and we are closer, we can have more opportunity to love. The more we love the more we are united, the more we are united, the more we love. A good example would be loving parents. They always desire to be close to their children because they can love them even more by protecting, providing, and educating them.
So also, those who love God seek to be with and please God. When we initially love God, we begin spending time in prayer and attending the Eucharist every Sunday. We start reading the Bible and learning about our faith. Yet, as we grow in love, we spend more time with the Lord, in prayers, hear the Mass more often, and are involved in ministries and community. However, we realize also that our unity with God is not perfect in this world. We need to work or go to school. We need to take care of our family. We need to attend to endless worldly affairs. Our hearts and love are divided.
However, one person loves God totally and undividedly, even in this world. She is Mary. Her life is wholly dedicated to loving Jesus, even from before His birth to the very end, the cross. She is never separated from Jesus in her life on earth. And thus, when she passed from this earth, her immense love, perfected by God’s grace, drew not only her soul but also her body into that union with God.
Mary’s assumption teaches us that union with God in heaven begins with our love here on earth. The more we love God here on earth, the easier we are drawn to heaven. Yet, how do we love God more if we also must take care of earthly matters? Indeed, we cannot pray all the time, but we can always please God by doing good and avoiding sins in everything we do. Through good moral life, we are united with God even daily. Though we are not always aware of God every second, we know that our lives and actions are oriented to God.
Surabaya
Valentinus Bayuhadi Ruseno, OP
Guide questions:
What do you have in mind when you hear the Assumption of Mary? What do you understand about this Marian dogma? What are the other three Marian dogmas? Do you have any special relationship with Mary? How do you see her?
How do you love God? How intense is your love for God? How do you improve your love for God? Do you pray often? How do you pray? Do you live a good moral life? Do you please God in your daily actions? Are you aware of God’s laws? Is there any sin that you are struggling with now?